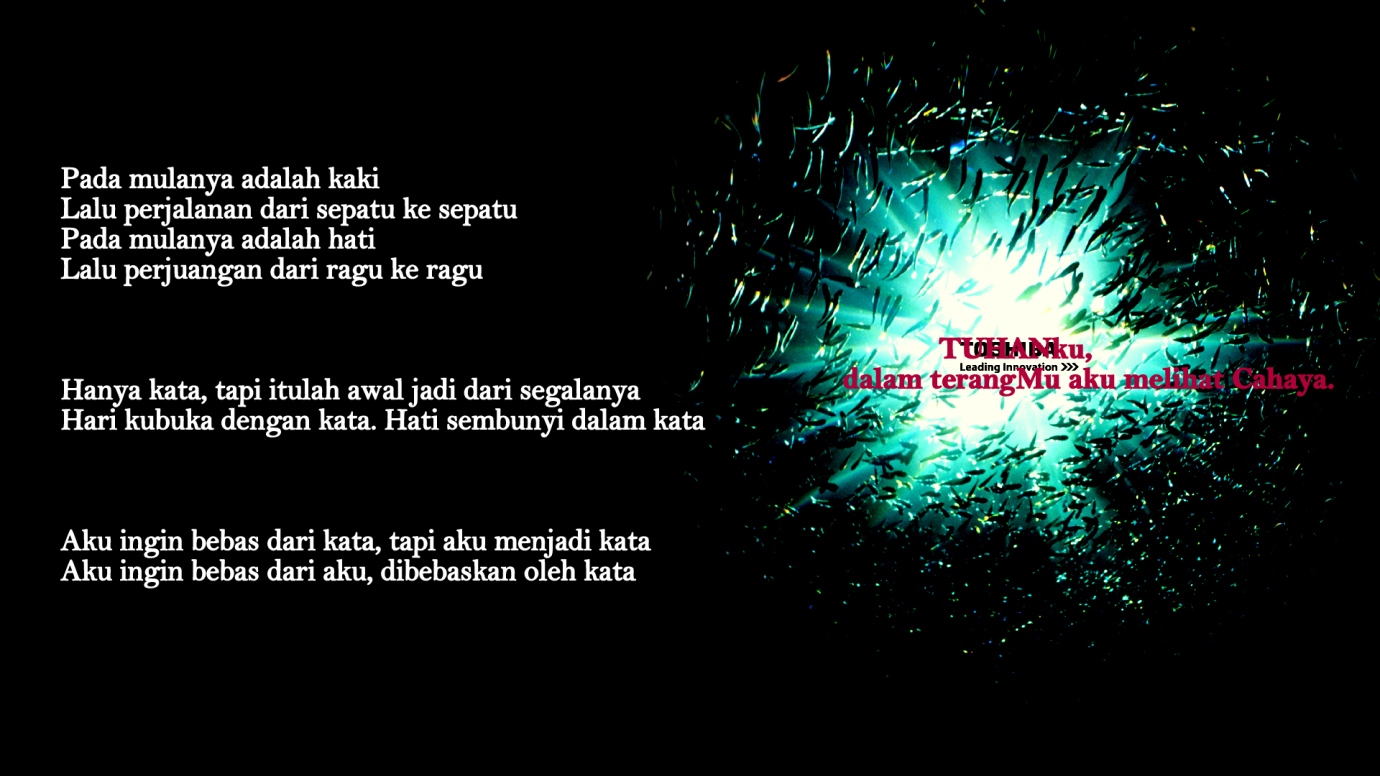Kita sedang hidup dalam sebuah zaman di mana kepribadian seseorang justru dinilai dari kualitas kata-katanya. Dengan berkata-kata, seseorang sanggup mengekspresikan harapan, cita-cita dan kompleksitas emosinya. Dengan kata, sebuah negara lahir; sebagaimana yang ditulis Ernest Renan, teoritikus Prancis dalam esainya “What Is A Nation?”.
Goenawan mohammad dalam salah satu catatan pinggirnya (Tempo, 31/01/2010) menyitir sajak Subagio Sastrowardojo pun demikian, Kita takut kepada momok karena kata/Kita cinta kepada bumi karena kata/Kita percaya kepada Tuhan karena kata/nasib kita terperangkap dalam kata. Dengan kata lain, kata (atau lebih tepatnya bahasa) bukan lagi sebagai sebuah term yang mati melainkan yang hidup dan kini justru telah tersistematisasi sedemikian rupa sehingga manusia ‘terperangkap’ di dalamnya. Hanya karena kata-kata, seseorang bisa dengan mudah memperoleh akses menjadi terkenal atau pun sebaliknya dijebloskan dalam penjara bahkan dihukum mati. Karena fungsi destruktif, diplomatif dan destruktif dari kata-kata yang secara esensial menegaskan eksistensi tersebut, maka manusia dimeterai sebagai makhluk yang memberi arti pada tanda-tanda sekaligus sanggup mengaburkan maknanya. Singkatnya, kata-kata telah sedemikian akrab dengan manusia yang kadang memandangnya terlampau akbar. Realitas berbicara bahwa secara ontologis, kata seringkali dikonfrontasikan dengan perbuatan yang secara etis mendahuluinya. Orang yang cenderung berbicara banyak tanpa aksi yang nyata mengingatkan saya pada sebuah pameo klise No Action Talk Only (NATO) di mana terdapat kecenderungan berlebihan untuk menyusun dan membangun dunia dari rangkaian kata. Teori Ruang Publik yang dianjurkan oleh filsuf berkebangsaan Jerman, Jürgen Habermas di mana aksi komunikatif dalam arena publik merupakan prioritas utama direlativisir bukan lagi sebagai media penyampai makna, melainkan untuk membentuknya.
Status Kata-kata dalam Perbuatan
Sebuah peribahasa Latin: “Verba Movent, Exempla Trahunt” (kata-kata menggerakkan teladan) menegaskan status kata-kata secara a prori membudayakan tindakan dengan maksud agar kata-kata itu memiliki roh atau daya ketika diucapkan kembali. Menyimak problem hidup dewasa ini, kita perlu jujur mengakui bahwa idealisme tersebut masih merupakan sebuah mimpi kosong. Praktek kampanye yang selain menghamburkan kata-kata, juga menelan anggaran yang besar; budaya masyarakat yang terlalu memprioritaskan kata-kata; dan juga kemapanan pers dalam eufemisme bahasa merupakan contoh yang menarik untuk kita pelajari bersama. Jika Anda menghadiri upacara kematian, di sana tampak kekaguman terhadap seseorang diproklamirkan. Muncul pertanyaan: Mengapa jasanya ini tidak diungkapkan ketika ia masih hidup? Mengapa kebiasaan memuji dan menyanjung orang yang tutup usia terjadi dalam perkabungan? Mengapa tidak ada sedikit keberanian untuk mengatakan apa adanya tentang orang yang telah meninggal termasuk kekurangannya? Saya yakin jika Anda belum pernah mengalami kematian mungkin sulit untuk menjawabnya. Di mana-mana kita jumpai aneka penghalusan makna (eufemisme) yang menghempas kita pada kebiasaan ‘bungkus-membungkus’ makna. Jika demikian, bagaimana mungkin kesejahteraan dan kebebasan berekspresi yang didambakan masyarakat kolektif menjadi niscaya dalam kata dan perbuatan apabila kita masih saja mempeributkan yang kabur-kabur?
Kemiskinan Kata-kata
Ketika berhadapan dengan sebuah sistem yang super organic (diwariskan secara turun-temurun) dan rigid (kaku), kecenderungan untuk bungkam merupakan pilihan yang dianggap wajar oleh manusia zaman ini. Tidak mengherankan jika masyarakat banyak mengeluh tentang profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas moral wakil-wakilnya baik di tingkat daerah maupun di pusat. Sorotan utama bahwa para pemimpin ternyata gugup dan gagap di hadapan sistem dan tradisi tertentu telah menjadi sebuah ramalan yang hampir pasti terlaksana. Bahkan di kancah agama pun demikian ketika doa dianggap hanya sebagai pendarasan kata-kata secara berkala tanpa ada upaya untuk menghayati makna. Selain itu, kita saksikan kenyataan adanya situasi keterbatasan masyarakat kecil untuk berkata-kata. Kaum pekerja wanita di manca negara yang diperkosa dan dianiaya, para petani yang dihimpit kebijakan impor beras, perdagangan wanita dan anak-anak, dan rintihan pedagang kaki lima yang dihimpit kenaikan harga sembako, merupakan contoh dari sekian banyak potret buram bangsa Indonesia. Kebangsaan kita akhirnya lebih cocok disematkan predikat ‘komunitas politik terbayang’ sebagaimana oleh Benedict Anderson. Orang lalu lebih cenderung untuk memojokkan diri lewat perbuatan yang tidak terhormat dan mengubur diri dalam kebanggaan masa lampau atau masa depan sebagai orang hebat ‘palsu’.
Kata-kata Menunjukkan Fakta
“Jika saya mengatakan setiap orang mengatakan demikian, artinya saya mengatakan demikian juga,” demikian Ed Howe mencoba menghantar kita khususnya para pemimpin zaman ini untuk semakin cerdas baik dalam berkata-kata maupun bertindak agar tidak menimbulkan kesenjangan dalam berbagai segi kehidupan perpolitikan bangsa ini. Adanya anggapan bahwa pohon yang tinggi di Indonesia bukan cuma terkena angin yang paling besar tetapi juga pohon yang harus dikapak, tidak menjadi sebuah alasan bagi kita untuk takut mengusahakan kebangsaan kita yang taktis dalam berkata-kata terlebih dalam jangkauan ruang manca negara. Menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang sanggup berkata-kata dan bertindak sekaligus mengandaikan adanya kerja ekstra baik dari pemimpin maupun dari rakyat sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi terhadap budaya berpikir kita yang senantiasa menjaga kemapanan konsep bahwa kata-kata menunjukkan kualitas kepribadian seseorang atau sekelompok orang. Di samping itu, hal mendasar lain yakni merosotnya kualitas dunia pendidikan di mana teori dan kuliah mimbar lebih diutamakan dibandingkan dengan praktek nyata selaras ilmu. Kurikulum Berbasis Kompetensi sering berujung mandul ketika berhadapan dengan kondisi sekolah atau universitas yang minim sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kualitas KBM. Hasilnya jelas, para pelajar dan mahasiswa begitu cerdas dalam berteori menggunakan kata yang muluk-muluk namun kelihatan jelas rasa keterkejutannya (cultural shock) ketika berhadapan dengan kompleksitas kenyataan yang sama sekali baru. Akhirnya saya mengajak semua saja, jika kita tidak mampu melakukan sesuatu yang berharga untuk dicatat, tulislah sesuatu yang berharga untuk dibaca. Dan jika kita menulis, “kita sedang memburu arti…,” Chairil Anwar menambahkan.